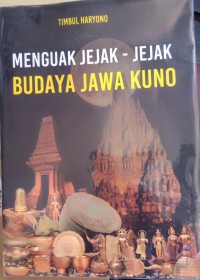“Jejak Waktu, Jejak Peradaban: Menafsir Ulang Jawa Kuno Bersama Timbul Haryono”
Judul: Menguak Jejak-Jejak Budaya Jawa Kuno
Judul asli: –
Penulis: Prof. Dr. Timbul Haryono, M.Sc.
Penerbit: Medang Heritage Society, Yogyakarta (2023)
Halaman: xxvi, 198 hlm., 27 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN: 978-623-96355-7-2
Resentator: Joko Setiyono, S.Sos
Ada kalanya sebuah buku bukan hanya berisi pengetahuan, tetapi membuka kembali percakapan panjang sebuah bangsa tentang siapa dirinya, dari mana ia datang, dan bagaimana ia sampai pada hari ini. Karya Timbul Haryono, Menguak Jejak-Jejak Budaya Jawa Kuno (Medang Heritage Society), termasuk yang demikian. Buku ini tidak meledak secara publik sebagai best-seller massal, tetapi bagi dunia kajian budaya Nusantara, ia berdiri sebagai salah satu tonggak penting yang menempatkan Jawa secara wajar: bukan sebagai entitas eksotik dalam kacamata kolonial, bukan pula sebagai nostalgia seremonial, tetapi sebagai peradaban yang tumbuh dari kesadaran ruang, masyarakat, dan kosmologi yang matang.
Timbul tidak menulis seperti pengelana romantik. Ia menulis seperti seorang peneliti yang sudah berpuluh tahun bergulat dengan artefak, inskripsi, candi, prasasti, bahasa, dan struktur sosial yang melahirkannya. Kalimat-kalimatnya kadang padat data, tetapi justru karena itu pembaca merasa bahwa ia tidak sedang diajak berkabur: ia diajak menapaki tanah yang nyata—tanah yang menyimpan jejak kaki raja, petani, seniman, pembuat prasasti, pengukir relief, dan orang kebanyakan yang berabad-abad lalu hidup di sebuah dunia yang masih dapat kita saksikan reruntuhannya hari ini.
Ada buku-buku sejarah yang menambah pengetahuan, dan ada pula yang mengubah cara kita membaca masa lalu. Menguak Jejak-Jejak Budaya Jawa Kuno karya Timbul Haryono termasuk kategori kedua. Karya ini bukan sekadar katalog peninggalan arkeologis, bukan pula glorifikasi Jawa sebagai “masa lalu yang megah,” tetapi sebuah usaha sistematis untuk meletakkan kembali sejarah Jawa Kuno ke tangan masyarakat—bukan hanya raja, bukan hanya koloni, bukan pula romantisisme mistik.
Seperti kita maklumi selama ini, gelanggang pemikiran yang sejak masa kolonial hingga awal Indonesia modern telah didominasi dua raksasa akademik yakni: F.D.K. Bosch, tokoh arkeologi Hindia Belanda, dengan gagasan bahwa negara Jawa Kuno adalah “mikrokosmos kosmis”—suatu dunia religius-politik yang berpusat pada raja. Dan R. Soekmono, arkeolog Indonesia awal kemerdekaan, yang berusaha menurunkan Jawa dari menara spiritual Bosch menjadi masyarakat rasional yang dapat dipahami dengan ilmu. Maka Timbul Haryono datang sebagai generasi berikutnya yang tidak sekadar melanjutkan, tetapi membuka ruang baca baru, lebih interdisipliner, lebih sosial, lebih terhubung dengan arus kajian budaya modern yang menempatkan:lingkungan, teknologi, masyarakat, ekonomi, dan konteks lokal sebagai fondasi peradaban. Dengan demikian, membaca buku ini bukan hanya mempelajari masa lalu, tetapi juga melihat bagaimana Indonesia merebut kembali agensi penafsiran sejarahnya sendiri.
Membawa Jawa turun ke tanah. Sejak paragraf awal, Timbul menolak memandang sejarah Jawa sebagai “sejarah mahkota”. Menurutnya, candi, prasasti, dan arca tidak akan pernah ada jika tidak ada masyarakat yang bekerja, makan, membangun, dan hidup di bawah struktur sosial tertentu. Ini kedengarannya sederhana, tetapi jika ditempatkan dalam sejarah ilmu, pernyataan itu sangat penting. Karena: Studi kolonial cenderung menempatkan kerajaan Jawa sebagai konstruksi kosmis yang abstrak. Studi awal Indonesia sering kali masih terbebani oleh kerangka narasi besar “raja dan dinasti”. Timbul memecah dua kutub itu, dan menunjukkan: bahwa sejarah tidak pernah lahir dari ruang ide, tetapi dari ruang permukiman, sawah, sungai, dan organisasi tenaga kerja. Dari sini tampak bahwa Timbul lebih dekat dengan arkeologi sosial, bukan sekadar arkeologi benda.
Candi sebagai arsip peradaban. Salah satu bagian paling kuat dari buku ini adalah cara penulis membaca candi bukan sebagai monumen mati atau ziarah spiritual semata, tetapi sebagai naskah sosial yang terbuka. Candi memiliki: denah mengandung sintaksis ruang, relief sebagai paragraf kehidupan, ukiran pekerjaan sehari-hari merupakan data kelas sosial, atasi dan orientasi bangunan adalah respons terhadap lanskap ekologis. Cara baca ini melampaui tradisi lama, karena: Bosch lebih banyak membaca simbolisme kosmologis. Soekmono membaca rasionalitas teknis dan sejarah perkembangan gaya. Timbul mengaitkan keduanya dengan struktur masyarakat dan ekonomi yang membuat candi mungkin. Dengan kata lain: Candi bukan warisan arsitektur raja. Candi adalah hasil tenaga masyarakat. Dan di sinilah ia berbeda paling jauh dari Bosch. Jika Bosch melihat raja sebagai pusat yang memancarkan ketertiban kosmos, Timbul menegaskan bahwa tatanan kosmos itu hanya bekerja lewat organisasi sosial manusia.
Bagi Bosch, negara adalah sebagai mikrokosmos. Dari sisi kolonial, F.D.K. Bosch membangun fondasi besar ilmu arkeologi Jawa dengan gagasan bahwa kerajaan Jawa Kuno adalah “negara-dewa” merupakan manifestasi daratan kosmis Asia klasik. Dalam kerangka Bosch: Raja adalah poros dunia. Kosmologi menentukan struktur negara. Masyarakat adalah pengikut dalam struktur religio-politik. Bosch melihat keagungan Jawa dari atas, dari langit simbol, dari metafisika. Dan karena posisi akademis kolonial abad ke-20 memang menempatkan sarjana Eropa sebagai “penerjemah dunia Timur,” pandangan Bosch menjadi dominan, bahkan lama setelah Indonesia merdeka. Banyak buku teks awal sejarah kebudayaan masih mengulang gagasannya. Timbul tidak membantah Bosch secara frontal, tetapi menggeser perspektifnya: Ia membawa pandangan dari langit turun ke tanah. Ia bertanya bukan hanya “apa makna kosmis raja,” tetapi juga “siapa yang membangun, bagaimana alokasi tenaga kerja, bagaimana logistik batu dipindahkan melalui sungai?” Pendekatan ini menjadikan analisis lebih demokratis dan sekaligus lebih empiris.
Sementara, Soekmono melihat rasionalisasi sejarah. Setelah kolonialisme runtuh, Indonesia mengalami periode baru dalam akademisi sejarah. R. Soekmono, generasi arkeolog pertama Indonesia, mulai menembus dominasi pemikiran metafisik Bosch. Soekmono mengembalikan: raja adalah pemimpin manusia biasa, kerajaan sebagai institusi sosial yang berkembang melalui pengalaman historis. Dan budaya merupakan sesuatu yang dapat diteliti melalui arkeologi-stratigrafi, tipologi, dan sejarah perkembangan gaya. Gagasannya menegaskan bahwa: “Jawa adalah masyarakat, bukan mitos.” Timbul banyak mewarisi garis rasional ini, tetapi ia mengembangkan lebih jauh: ia menambahkan lensa multidisipliner yang kuat: baik dari antropologi, ekologi, studi pemukiman, historiografi poskolonial, dan materialitas. Jika Bosch bicara dari menara metafisika, Soekmono bicara dari laboratorium arkeologi, maka: Timbul bicara dari pasar, sawah, bengkel batu, jaringan desa, dan sistem logistik. Pendekatannya jauh lebih sosial.
Arkeologi bukan ilmu batu tetapi ilmu tantang kerja manusia. Bagian tengah buku ini memperlihatkan bagaimana Timbul sering memulai dari hal kecil dari kelokan saluran air, dari jenis batu yang dipakai di kaki candi, dari perubahan gaya ukir rambut tokoh dalam relief dan kemudian membangun argumen besar. Ia menunjukkan bahwa: perubahan teknis menandakan perubahan organisasi tenaga kerja, perubahan gaya ukir adalah menandakan mobilitas pengrajin, penempatan candi dapat menandakan strategi ekologis dan politik ruang, variasi prasasti bisa menandakan beragam sistem administrasi dan pajak. Dengan pendekatan ini, pembaca merasakan bahwa: arkeologi adalah studi tentang kehidupan, bukan sekadar studi tentang peninggalan. Inilah pergeseran paling modern dalam studi arkeologi Jawa.
Ruang hidup sebagai sumber sejarah. Sejarah Jawa selama ini sering dilihat sebagai rentetan nama raja: Sanjaya, Panangkaran, Sindok, Dharmawangsa, Airlangga, Kertanegara, Raden Wijaya. Tetapi Timbul mengajukan angle lain: Bagaimana keterhubungan desa-desa penopang candi? Bagaimana tenaga kerja diorganisasi? Bagaimana logistik dan distribusi hasil pertanian menentukan kekuatan kerajaan? Bagaimana permukiman tumbuh di bawah orbit pusat kekuasaan? Dengan demikian: Kerajaan bukan entitas abstrak, melainkan jaringan kerja dalam ruang. Dan di titik ini, Timbul memperlihatkan bahwa: perubahan lingkungan, sistem irigasi, pola migrasi penduduk, atau maraknya perdagangan lebih menentukan nasib kerajaan daripada figur raja tertentu. Ini berbeda sekali dari historiografi kolonial yang menekankan: kharisma raja, legitimasi kosmologis, sakralitas singgasana. Yang bagi Timbul hanyalah puncak gunung es. Sedang es itu sendiri adalah: masyarakat dan struktur tenaga kerja yang menopang semuanya.
Jika Soekmono adalah “arsip besar” dari arkeologi Indonesia generasi pasca-kemerdekaan—yang berupaya membangun fondasi metodologis ilmiah arkeologi Nusantara—dan Bosch adalah penjuru besar arkeologi kolonial yang menempatkan Jawa dalam kerangka Indianisasi, maka Timbul Haryono hadir sebagai pembaharu yang mengembalikan Jawa kepada rumah epistemiknya sendiri.
Ada tiga titik beda utama yang strategis.Pertama, Orientasi Teoretis. Bosch menekankan pengaruh besar India sebagai sumber formasi kebudayaan Jawa. Struktur analisisnya adalah diffusionist, berpijak pada gagasan bahwa Hindu–Buddha adalah “pengetahuan besar” yang masuk melalui elite dan kemudian mengalir menjadi kebudayaan istana. Soekmono mencoba menempatkan kebudayaan Jawa lebih dalam koheren internal—meski tidak menolak Indianisasi, ia menempatkannya dalam konteks interaksi, bukan sekadar peniruan. Timbul Haryono melampaui keduanya: ia menyatakan bahwa inspirasi India memang hadir, tetapi wujud budaya Jawa Kuno justru merupakan artikulasi kreatif asli, hasil transformasi alam, simbolisme, kosmologi kerja para seniman, dan ideologi masyarakat lokal. Timbul mengoreksi asumsi lama bahwa Jawa hanya meniru, dan ia mendasarkan koreksi itu bukan pada retorika, tetapi pada data formal, perbandingan ikonografi, penelusuran teknik produksi, pola bengkel seni, hingga analisis konteks sosial para pengrajin.
Kedua, Titik Tekan Kajian. Bosch fokus utama pada kontak budaya dan Indianisasi; Soekmono fokus utama pada Stratigrafi, sistematika arkeologi Indonesia, konstruksi narasi ilmiah; Timbul Haryono fokus utama pada Morfologi, gaya, teknik produksi, basis sosial-ekonomi seniman dan masyarakat. Jika Bosch menulis sejarah dari atas—dari raja, agama, filsafat, dan teks—Timbul justru menulis dari bawah: dari pemahaman mengapa tanganMpu tertentu menghasilkan garis lekuk tertentu.
Ia membawa seni Jawa keluar dari “langit wacana agama” dan menurunkannya kembali menjadi hasil kerja manusia biasa: seniman, pandai, pematung, perajin, pengrajin logam, dan organisasi produksinya.
Ketiga, Basis Epistemik. Inilah yang paling penting: Timbul menunjukkan bahwa seni Jawa Kuno bisa dipahami tanpa harus menggunakan perangkat tafsir India sebagai pusat rujukan utama. Ia menggeser paradigma:dari ”Jawa sebagai anak India” menjadi ”Jawa sebagai penafsir kreatif terhadap arus global”. Dalam atmosfer akademik kita, pergeseran ini signifikan.
Timbul Haryono mengajukan koreksi bukan melalui polemik, melainkan melalui penelitian sistematis berbasis data formal dan komparatif. Tiga pendekatannya paling menonjol: (1) Analisis Morfologi Sistematis Timbul tidak sekadar menyebut “patung ini bercorak Jawa”—ia menguraikan: perbandingan proporsi wajah, pinggang, lengan, perspektif tubuh, hingga gaya sikap, pengulangan motif tertentu bertahun-tahun, yang menunjukkan adanya pola lokal yang konsisten, bukan turunan langsung dari India. Dengan metode ini, ia memperlihatkan bahwa: seniman Jawa Kuno memiliki pola estetika khas yang stabil, dan berlangsung konsisten selama berabad-abad, sementara pengaruh India lebih berfungsi sebagai lapisan ikonografis atau religius.
(2) Metode Cross-Referencing Antar-Situs Bosch dan Soekmono sering menjelaskan situs dalam konteks historis dan kronologis. Timbul menambahkan langkah baru: membandingkan gaya antar-situs (Dieng, Kedu, Prambanan, hingga Jawa Timur), menelusuri apakah gaya tertentu hanya hadir pada region tertentu, kemudian membaca konteks sosial di baliknya. Pendekatan ini mendekatkan seni Jawa pada sosiologi visual, bukan hanya arkeologi formal. (3) Analisis Basis Produksi dan Dunia Perajin. Inilah aspek yang Bosch dan Soekmono hampir tidak masuki: bagaimana seni diproduksi. Timbul meneliti: keberadaan bengkel pertukangan, organisasi kerja perajin, patronase istana, bangsawan, dan pemuka agama, kontrol estetika yang menentukan bentuk dan fungsi karya. Ia menunjukkan bahwa bentuk seni tidak hanya ditentukan agama atau mitologi, tetapi juga oleh struktur ekonomi dan relasi produksi pada masa itu. Dengan cara ini ia menempatkan seni Jawa Kuno sebagai: aktivitas sosial, profesi, tradisi estetika regional, sekaligus bagian dari sistem ekonomi pra-industri. Dalam tradisi sejarah seni Indonesia, ini adalah lompatan intelektual besar.
Timbul tidak sedang menolak hubungan budaya dengan India. Ia dengan elegan mengatakan: India memberi bahasa simbol, nama-nama dewa, strukturalisasi kosmologi. Tetapi tubuh fisik seni—gaya, proporsi, bentuk figuratif—itu lokal. Ia menunjukkan dengan contoh: arsitektur Jawa tidak mengadopsi sistem mandala India secara literal, banyak ikonografi menampilkan karakter tubuh yang lebih pendek, lebih padat, dan lebih realistis, sesuai karakter tubuh manusia Jawa, pola ornamentasi menampilkan flora Jawa, bukan flora India. Dengan demikian, Indianisasi adalah: bukan induk tunggal, melainkan salah satu medium dalam proses lokalitas kreatif. Ini menandai pergeseran paradigma: dari “transfer budaya” menjadi “dialog kreatif antar-peradaban”. Dalam historiografi arkeologi, hal ini setara dengan membawa Jawa kembali menjadi subjek sejarahnya sendiri, bukan objek dari sejarah peradaban lain. Timbu, mengkoreksi Indianisasi: bukan menolak, tapi menempatkan secara adil.
Pembacaan Ontologis: Seni Jawa sebagai Pandangan Hidup. Bosch menafsir seni Jawa sebagai refleksi kosmologi India. Soekmono membacanya sebagai sistem keagamaan dan kegiatan budaya masyarakat Jawa Kuno. Timbul melangkah lebih jauh: ia menunjukkan seni sebagai cara hidup. Dalam buku ini bisa dibaca gagasan bahwa: seni adalah struktur kehidupan mental, ingatan masyarakat Jawa disimpan dalam bentuk visual, seni menjadi “pengikat makna” antara alam, manusia, dan ketuhanan. Dalam tradisi pemikiran Jawa, rasa adalah pusat pengetahuan.
Dan Timbul—tanpa menuliskannya secara polemis—sebenarnya membawa seni kembali pada inti kosmologi Jawa: harmoni, keseimbangan, keseluruhan. Dengan demikian, Menguak Jejak-Jejak Budaya Jawa Kuno bukan sekadar buku sejarah seni, tetapi sebuah teori kebudayaan Jawa.
Relevansi bagi perdebatan arkeologi dan kajian budaya masa kini. Mengapa buku ini penting bukan hanya sebagai literatur akademik, tetapi juga sebagai pengetahuan budaya bangsa? (a) Indonesia Perlu Narasi Kulturalnya Sendiri. Selama satu abad, narasi yang dominan adalah: Jawa berkembang karena India datang. Buku ini mengoreksi dan menambahkan: Jawa berkembang karena Jawa mampu menafsir dunia luar dengan kreativitas internalnya. Dalam atmosfer global saat ini—ketika banyak negara membangun identitas budaya baru—narasi Timbul sangat relevan.
(b) Meneguhkan Sejarah Kreativitas Nusantara. Di tengah narasi modern bahwa teknologi dan seni adalah produk luar negeri, buku ini mengingatkan: Jawa sudah punya sistem teknologinya sendiri, ada manajemen galeri abad ke-8, ada konstruksi profesionalisme seni jauh sebelum dunia industri. (c) Model Baru Penulisan Sejarah Kesenian Timbul memberi contoh metodologi yang bisa dipakai untuk: seni Bali, seni Aceh, Batak, Kalimantan, seni tradisi Nusa Tenggara, dan lain-lain. Sejarah seni Nusantara bisa ditulis dari perspektif masyarakatnya sendiri, bukan dari lensa difusi besar belaka.
Catatan redaksional, sebagai buku untuk publik ilmiah populer, ada catatan kecil yaitu: Sebaran argumen terkadang terlalu padat. Sebagian bab menuntut pembaca memiliki: pengetahuan ikonografi, sedikit wawasan arkeologi, pemahaman metode perbandingan formal. Bagi mahasiswa pemula atau pembaca awam, beberapa bagian mungkin terasa “rapat” secara akademik. Namun bagi pembaca yang siap—itulah keunggulannya.
Mengembalikan Jawa ke jati dirinya sendiri. Bosch membuat kita menyadari bahwa Jawa tidak hidup sendiri. Soekmono membuat arkeologi menjadi ilmu yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.Timbul Haryono kemudian menambahkan batu bata paling penting: bahwa seni Jawa adalah hasil kreativitas kultural manusia Jawa sendiri. Buku ini mengajarkan bahwa: kebudayaan tidak lahir dari peniruan, tidak pula tumbuh sebagai salinan, tetapi melalui proses penafsiran kreatif, ketika manusia memadukan pengaruh luar dengan rasa, logika, dan pengalaman dunia-nyata yang mereka jalani. Oleh karena itu, Menguak Jejak-Jejak Budaya Jawa Kuno adalah bacaan yang tidak hanya mengajarkan sejarah seni, tetapi juga mengajarkan kedewasaan berpikir sebagai bangsa. Ia mengingatkan: bahwa globalisasi bukan ancaman, tetapi peluang untuk mengekspresikan jati diri, jika kita mampu membaca arus luar dengan kecerdasan lokal seperti leluhur kita dahulu. Dan pada akhirnya, seperti pesan yang tersirat dari buku ini: kebudayaan Jawa bertahan bukan karena ia menutup diri, tetapi karena ia mampu menafsir, mengolah, dan mencipta ulang dunia luar dengan bahasanya sendiri. Buku ini bisa dicari dan dibaca oleh para pemustaka Perpustakaan ISI Surakarta, lokasi penyimpanan dengan nomor panggil: 930.598 2 TIM m.[]